Riza Primahendra: Bonus Demografi Akan Jadi Bencana Kalau Tak Ada Lapangan Pekerjaan

Jakarta, Inako
Direktur Amerta Pajar Indonesia Riza Primahendra mengatakan bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif akan menjadi masalah besar kalau tidak diiikuti dengan penciptaan lapangan kerja. Ketika mereka tidak bisa bekerja, maka aspek politik dan sosial akan berkembang menjadi sangat dinamis dan tekanan terhadap ekonomi juga semakin besar.

Hal ini diungkapkan Riza dalam Workshop CSR Outlook 2020 di Centennial Tower, Jakarta, belum lama ini. Ia mengatakan, selain masalah lapangan kerja yang minim, problem lain dihadapi bangsa ini adalah adanya kesenjangan kualitas dan konsentrasi yang asimitris antara Jawa dan luar Jawa, Urban and Rural (Perkotaan dan Desa).
Simak video Inatv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia maju.
“Saya lihat ini akan menambah kompleksitas kita dari bonus demografi. Kita memang melihat beberapa waktu terakhir ini, Presiden kelihatan seolah-olah bahwa pada aspek yang non-ekonomi seolah-olah pasif. Tapi Presiden sekarang justru fokus menciptakan lapangan kerja,” tegas Riza.
Menurut Riza, kalau tidak ada lapangan kerja, maka bangsa ini akan mengalami masalah besar. Masalah tersebut tidak hanya terjadi dalam satu hingga dua tahun, tetapi bisa berlangsung hingga 30 tahun.
“Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, maka paling tidak kita punya masalah selama 30 tahun. Karena bonus demografi itu kan sepanjang usia produktif. Begitu tidak ada kerja maka bencana itu akan terjadi selama 30 tahun. Ini yang harus kita pahami bersama,” tambah Riza.

Riza mengakui bahwa saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan bantuan dalam bentuk program sosial perusahaan atau CSR, tetapi juga diminta untuk menyediakan pekerjaan.
Ia mengambil contoh soal program bantuan persekolahan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan melalui CSR. Menurut Riza, membantu anak-anak sekolah tidak cukup, sebab yang paling dibutuhkan di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia produktif adalah lapangan pekerjaan.
“Membantu sekolah tentulah tidak cukup, karena orang butuh pekerjaan. Dan mungkin tantangan terbesar kita sekarang adalah apakah, kalau kita banyak program CSR, yang ada di pulau-pulau kecil, pesisir, masyarakat hutan, apakah di situ dibutuhkan SD, SMP, SMA, hingga akademi,” tegas Direktur Amerta ini kepada Inakoran.com.
Menurut Riza, pendidikan dan pesekolahan tidak identik. Persekolahan merupakan bagian dari pendidikan. Ia mengacu pada pengalaman Amerta saat mendampingi sejumlah anak di pedalaman Papua.
“Saya berangkat dari pengalaman Amerta di Papua. Di sana anak yang tamat SMA, terkadang merasa tidak berguna setelah lulus SMA. Soalnya, yang mereka butuhkan adalah bisa membaca dan berhitung. Kalau mereka hidup di pesisir, maka mereka harus bisa memperbaiki mesin Johnson yang rusak, bisa memperbaiki jaring yang rusak. Sementara kalau mereka yang ada di hutan, mereka harus tahu bagaimana mengolah hasil hutan secara berkelanjutan. Jadi disini bukan soal Ijazah. Tetapi saya lihat bahwa banyak sekali pengambil kebijakan yang menganggap bahwa pendidikan itu identik dengan persekolahan. Dan ini saya melihat tidak menyelesaikan masalah bonus demografi,” tegas Riza.
Membangun Mimpi
Hal senada juga diungkapkan oleh Simon Rafael, peserta Workshop dan praktisi pendidikan. Rafael mengatakan bahwa ada kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang ada di kampung atau desa, bila anaknya bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun meraih pendidikan tinggi tidak dengan sendiri menyelesaikan pesoalan, karena ujung-ujungnya tetap soal ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Saya sepakat dengan pernyataan bahwa kita mengalami penderitaan selama 30 tahun, kalau gagal mengelola sumber daya manusia, utamanya gagal menyediakan lapangan pekerjaan,” tegas Rafael.
Terkait sejauhmana pentingnya pendidikan bagi anak-anak, Rafael mengacu pada pengalamannya saat mendampingi anak-anak di pedalaman Kalimantan. Ia mengakui bahwa saat melakukan wawancara terhadap sejumlah anak, mayoritas dari mereka justru tidak mau melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan seorang anak kelas 3 SMA, saat ditanyak soal cita-cita, hanya menjawab ingin menjadi penambang emas.
“Namun di sisi lain, saya juga dapat jawaban yang berbeda, ketika ditanya soal cita-cita kepada seorang siswa kelas 2 SMP. Ia ingin sekolah supaya jadi perawat. Kalau sudah jadi perawat, maka dia bisa kembali ke desa, dan paling tidak bisa membantu merawat orangtunya,” tegas Rafael.
Menurut Rafael, tantangan yang dihadapinya sebagai praktisi pendidikan untuk anak-anak di pedalaman adalah bagaimana dirinya dan timnya membangun mimpi. Karena itu, ketika pihaknya berbicara tentang masalah pendidikan, maka itu tidak ada kaitan dengan persekolahan, tetapi lebih terkait membangun mimpi.
Ia mengakui mimpi setiap anak berbeda. Oleh karena itu, ketika seorang anak SMP mempunyai mimpi untuk menjadi perawat, maka yang harus dilakukan dalam kegiatan pendampingan adalah bagaimana mendorong anak tersebut untuk membuat sebuah rencana agar bisa menjadi seorang perawat.
“Menurut kami, di situlah konsep pendidikan, yakni mengarahkan seorang anak untuk meraih mimpinya. Karena itu, fokus kami terhadap anak-anak di pedalaman dan pedesaan, bukan diarahkan ke persekolahan, tetapi membangun minpi mereka. Itu yang menjadi konsentrasi kami saat ini. Kami coba latih dan menumbuhkembangkan mimpi anak-anak di area-area tempat kami berada,” tegasnya.







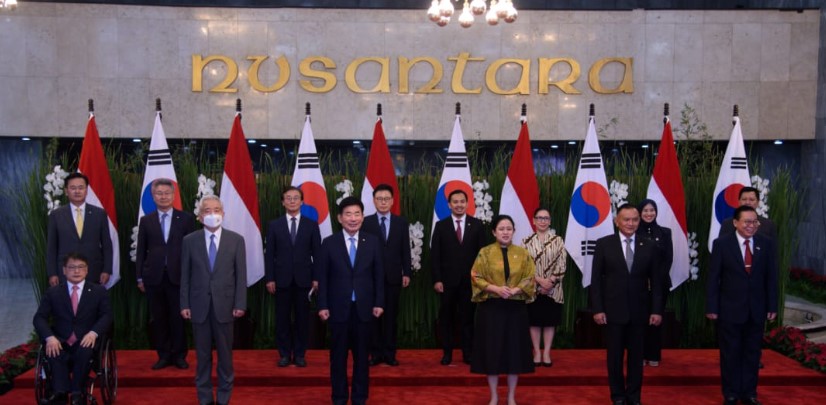






KOMENTAR