Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Nasional

Oleh: Dian Kresna (DianKresna Foundation)
Kebijakan ekonomi Indonesia sangat liberal. Ini sebagai dampak dari kebijakan eknomi orde baru yang didirikan dengan ajaran teks Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia.
Padahal, ajaran neoliberal jelas-jelas adalah pasar persaingan sempurna. Dampaknya kegiatan ekonomi Indonesia membuat orang kaya makin kaya dan sebaliknya. Singkatnya memperlebar kesenjangan, ada gap yang besar antara elite dan rakyat kecil.
Menurut Mubyarto, selama orde baru dan (menurut penulis sampai detik ini), perekonomian Indonesia lebih menggunakan metode deduktif, dengan mempelajari secara teoretis ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya.
Kebijakan ekonomi liberal jelas bertentangan dengan semangat para pendiri Republik yang tertuang dalam UUD 1945 terutama asas ‘demokrasi ekonomi’. Di dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat adalah paling utama, bukan kemakmuran satu individu atau kelompok saja seperti dalam ekonomi liberal.
Oleh karena itu, salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian nasional menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana konsentrasi dan penguasaan aset dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan berkelanjutan.
Semua ini hanya bisa terwujud kalau secara konsisten pemerintah kembali pada amanat UUD 1945 yakni membangun demokrasi ekonomi dengan berlandaskan “sistem ekonomi kerakyatan”.
Inilah tantangan bangsa Indonesia, bagaimana membangun sistem ekonomi yang didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Suatu sistem ekonomi berbasis kerakyatan (ekonomi kerakyatan).
Sistem ekonomi kerakyatan adalah produk hukum yang mengatur perikehidupan ekonomi nasional terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 pada:
Pasal 27 ayat (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
Pasal 28: kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan UU;
Pasal 31: negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;
Pasal 33: ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat (3) bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
Pasal 34: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Nilai Dasar dan Substansi Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang tujuannya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah Ketuhanan, bahwa kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
Kemanusiaan berupa pemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat bersama untuk mewujudkannya, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
Kepentingan nasional (nasionalisme ekonomi), yang menuntut urgensi perekonomian yang tangguh, dan mandiri;
Kepentingan rakyat banyak (demokrasi ekonomi) bahwa demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; dan
Keadilan sosial, yaitu keseimbangan yang efisien dan adil antara perencanaan dan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas dan bertanggungjawab.
Substansi ekonomi kerakyatan ada di pasal 33 yang dijabarkan dalam tiga hal.
Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Hal ini tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, namun tak kalah pentingnya sebagai dasar kepastian keikutsertaan masyarakat menikmati hasil produksi (sejalan dengan pasal 27).
Kedua, partisipasi dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar (dipertegas oleh pasal 34).
Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi harus berlangsung di bawah penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan menjadi subjek ekonomi.
Unsur yang ketiga ini mendalilkan perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam faktor-faktor produksi nasional (modal) baik modal material, modal intelektual dan modal institusional.
Lalu apa ciri suatu ekonomi bisa dikatakan ekonomi kerakyatan?
Pertama, menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, operatornya BUMN.
Kedua, efisiensi ekonomi yang didasarkan pada keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, sampai kelestarian lingkungan.
Ketiga, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar.
Keempat, koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah yang menyebabkan koperasi sebagai bangun yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan.
Kelima, pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk perusahaan (perseroan).
Di antaranya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik atau anggota koperasi. Inilah ajaran Hatta bahwa dalam koperasi tidak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja untuk menyelenggarakan keperluan bersama.
Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
Peran koperasi sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Selama ini industri besar terbukti tidak bisa menjadi pelaku tunggal memecahkan kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan semakin lebar.
Di tengah espektasi yang tinggi, kondisi koperasi kita masih lemah dan inilah yang harus ditata ulang. Peran koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional perlu diterjemahkan bukan saja dalam kebijakan publik, tak kalah penting dan ini yang paling bermasalah saat ini adalah memastikan kebijakan itu berjalan.
Oleh karena itu, pengembangan koperasi harus diletakan sebagai kepentingan ekonomi nasional yang tertinggi dimana pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten.
Konsep pengembangan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus mempunyai perspektif peran aktif seluruh komponen masyarakat; kebebasan berusaha, berkreasi dan berinovasi; kesempatan yang sama dalam akses teknologi dan informasi; sistem ekonomi yang terbuka dan efisien; dan mekanisme pasar yang berkeadilan.
Salah satu yang harus diperhatikan untuk mencapai hal tersebut harus dimulai dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas baik K/L teknis yang membidangi koperasi maupun K/L terkait harus punya nasionalisme ekonomi, memiliki kapasitas yang mumpuni maupun teknis yang kuat.
Selanjutnya penguatan manajemen dan personalia di tingkat pengurus koperasi harus juga dibenahi. Pendekatan semacam ini diharapkan menjamin terwujudnya ekonomi kerakyatan yang lebih adil dan merata dan berdaya saing untuk memenangkan persaingan global ditengah desentralisasi pembangunan untuk memaksimalkan potensi daerah.
Dalam perkembangan, muncul UMKM dan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi 2020, UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% (senilai Rp8.573,89 triliun).
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
Jumlah UMKM yang banyak, juga tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan ini direspon pemerintah dengan program dukungan UMKM diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, kredit usaha rakyat, gerakan nasional bangga buatan indonesia (Gernas BBI), digitalisasi pemasaran UMKM, bahkan strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja.
Hal yang terakhir ini menuai pro kontra di masyarakat. Pihak yang kontra memandang UU Ciptaker ini hanya menguntungkan para pengusaha besar, koperasi dan UMKM akan semkain tersingkir.
Covid 19 mendorong shifting dari offline ke online. Hal ini menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196,7 juta orang.
Dukungan, kerjasama, dan kolaborasi membangun koperasi dan UMKM berbasis teknologi perlu segara di buatkan peta terpadu dan dukungan penuh dari elemen bangsa terutama dan memang yang bertanggung jawab adalah pemerintah.
TAG#dian kresna, #dian kresna foundion, #pembangunan ekonomi nasional
216883348
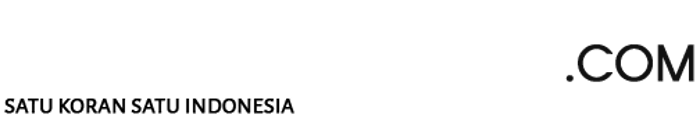
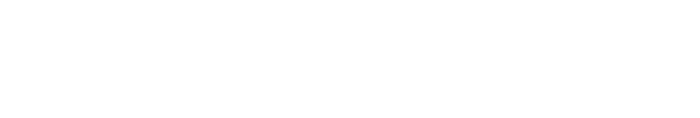










KOMENTAR