Menolak Premanisme, Mengadu Kepada Rakyat

Bagian 1 dari 2 tulisan
Oleh: Suryadi
Pemerhati Budaya dan Kepolisian
JAKARTA, INAKORAN
Premanisme dimaknai oleh masyarakat sebagai penganut tindakan memaksa diikuti oleh kekerasan verbal atau fisik (memalak), dengan maksud dan tujuan meminta dan menguasai sesuatu yang bukan haknya.
Akhir-akhir ini yang semacam ini, termasuk berebut menguasai pengamanan lahan, kerap mengemuka lengkap dengan keributan antarkelompok.
Baru-baru ini, seorang petinggi suatu daerah, menyatakan tempat salah satu kejadian peristiwa (TKP) premanisme yang masuk dalam wilayah administratif pemerintahan daerah yang dia pimpin, tak memiliki aparat terdepan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Terakhir malah dikatakan, warga di kampung itu, tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Tentu saja, hal semacam ini dapat mengundang tanya, benarkah pertumbuhan premanisme tidak terpantau, sehingga, wajar saja seolah mengagetkan. Benarkan demikian?
Adalah pasti, bahwa masyarakat yang terbina tanggap terhadap ketidakberesan di lingkungannya merupakan langkah dini pertama menolak kehadiran dan bertumbuhnya suatu kriminal, termasuk
premanisme di wiayah domisilinya.
CERITANYA, baru-baru ini penulis ngamen. Oleh satu sub satuan kerja besar dari suatu institusi aparat penegak hukum (APH), pekan lalu penulis didaulat memberi pembekalan kepada sekitar 200 pejabat institusi tersebut setanah air.
Dengan menjadikan Pemimpin, Komunikasi, dan Pers sebagai pisau bedah, saya menjadikan premanisme secara sosiologis (bukan hukum positif), dalam suatu penanganan menjadi contoh penindakan yang kaget-kagetan.
BACA:
Usai acara pembekalan singkat yang sempat diwarnai dua penanggap atas permintaan penulis dan satu penanggap murni atas inisiatifnya sendiri, seorang perwira tinggi yang juga doktor hukum, mendekati penulis dan mengajak berdialog.
Boleh jadi, dia tertarik dengan sajian penulis, yang antara lain:
Mengetengahkan upaya gotong-royong yang kian menipis pada warga Indonesia yang beragam etnis ini; Akan tetapi, dia juga menolak sebutan premanisme bila dibawa-bawa ke ranah penegakkan hukum. Sebab, premanisme tidak diatur dalam hukum positif pidana (KUPH) Indonesia, dan oleh karena itu harus diluruskan.
Penulis mencoba melengkapinya. Kemudian, membiarkan dia meluncur dengan pertanyaan, “Apa pendapat penulis tentang upaya institusinya dalam menghadapi masyarakat?”.
Dalam balutan charming-nya yang mengingatkan penulis kepada seorang seniornya yang boleh jadi ia kenal pun tidak, ia terkesan begitu ramah tak dibuat-buat dengan keekspertan dalam penegakan hukum dan pendekatan sosial.
Melalui tulisan ini, penulis merasa lebih leluasa berusaha merespon dengan jawaban kembali kepada masyarakat sebagai pemilik “habitat” peristiwa pemaksaan dengan kekerasan (baca: premanisme).
Penulis merasa masyarakat yang terbina yang sesungguhnya mampu secara dini menganulir kejahatan apa pun yang tumbuh dan berkembang di wilayah domisili mereka, termasuk premanisme.
Sementara pemerintah, terutama Pemerintah Daerah secara rutin berfungsi membina menumbuhkan keberanian untuk mencegah tumbuh-kembangnya suatu ketidakberesan (baca: kriminal atau penyakit masayarakat apa pun).
Pada saat yag sama APH menindak sesuai hukum positif, bila peristiwa tersebut tak lagi dapat dicegah secara dini alias benar-benar pecah menjadi peristiwa.
Dengan demikian, tindakan bersama secara dini sebelum menjadi embrio kriminal dapat dilakukan bersama secara dini. Maka, pencegahan (peremptif dan preventif) lebih utama ketimbang bila sesuatu telah terjadi.
Keterpaduan yang bukan musiman, yakni antara masyarakat dan pemukanya serta penguasa adminsitratif pemerintah setempat dan aparatnya yang peka dengan APH polisi berikut personel yang yang peka, tegas bertindak, dan human dalam pendekatan.
BACA:
Menipisnya Gotong Royong
DIAKUI atau tidak, mungkin sejak pembangunanisme (baca: apa pun syah ketika dihadapkan pada Pembangunan) melingkupi segenap negeri ini, budaya gotong-royong sudah semakin terpinggirkan.
Kemajuan teknologi tidak diantisipasi oleh rekayasa sosial atau mungkin rekayasa sosial ada tapi tertinggal jauh dari pembangunanisme.
Pebangunan karakter manusia tidak lagi sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan, dan filosofi hidup bangsa yang telah lama disepakati sebagai dasar negara.
Karya luhur anak bangsa ini, terasa seperti mubazir, lantaran cuma diakui oleh banyak warganya secara verbal belaka. Bahkan, jangan-jangan ada yang menggapnya sudah kuno!
Seorang teman yang akrab dengan teknologi maju dan penyutradaran film risau (lebih kurang sama risaunya dengan penulis) melihat kemajuan teknologi dewasa ini.
Sebab, kemuajuan teknologi --yang sesungguhnya memang tak bisa ditolak-tolak dan berciri pekat cepat dan mudah alias cepat saji itu--, tidak dibarengi oleh antisipasi yang efektif bagi kecerdasan emosi dan moral. Akibatnya, jadilah teknologi maju berkembang liar di tangan manusia-manusia yang pintar secara tak terkendali!
Di Tiongkok, dalam amatannya, kemajuan teknologi jauh meninggalkan Indonesia yang lebih cerdik meniru –metode dalam pedidikan anak-anak.
Tetapi, di negeri tersebut yang sering disentimeni oleh warga bangsa ini, sulit ditemukan generasi penerus (anak-anak dan remaja) asyik bergadget-ria, terutama di saat-saat senggang atau di ruang-ruang publik. Sebab, menurutnya, pemerintah di sana punya kebijakan sendiri yang memang efektif dipatuhi untuk itu.
Dengan kondisi seperti itu, wajar saja bila kini di sini gampang ditemukan mereka –tak muda tak dewasa-- yang lebih reflek sharing ketimbang thingking before sharing. Penulis kerap menjumpai di atas gerbong kereta rel listrik (KRL), kala sempit berdesak-desakan sekalipun, para penumpang lebih asyik bergadget-ria sambil duduk atau berdiri sekalipun.
Sambil berdiri pun, mereka tetap asyik bergadget-ria. Mungkin dalam tiap formasi gerbong penumpang, lebih banyak penumpang yang bergadget-ria ketimbang mereka yang membiarkan gadgetnya tetap di saku atau di dalam tas. Selebihnya, penumpang yang lain (entah pura-pura atau sungguhan) memilih tidur ketimbang bangun, lantas mempersilakan penumpang yang lebih layak duduk ketimbang dirinya untuk menempati kursi panjang yang mereka tempati.
Lebih celaka lagi, kerap dijumpai pemandangan mencolok kala jam-jam KRL tak begitu dipadati penumpang. Pernah, seorang Ibu muda, dengan dua orang anaknya, di kursi panjang gerbong KRL, asyik dengan gadget masing-masing.
Si Ibu asyik dengan Hp-nya sambil tertawa-tawa tertahan-tahan. Sementara seorang anak laki-lakinya yang mungkin belum tamat SD, berulang kali memerlihatkan mimik emosional dalam bergadget-ria. Seorang anaknya yang lebih kecil tidur-tiduran asyik pula dengan gadget di tangan. Ibu dan kedua anak asyik sendiri-sendiri.
Ketiganya secara emosional telah terfasilitasi oleh gadget. Labtas, siapakah penyedia gadget itu?
Apakah ada hubungan kegilaan pada teknologi cepat saji itu dengan menipisnya gotong-royong?
Untuk menjawabnya, tinggal pilih saja, lebih dulu melakukan survei pembuktian demi berbicara atas nama data, atau membiarkan kegilaan itu terus berlangsung hingga terbina berperilaku asosial?
Yang jelas, Bung Hatta, salah seorang bapak pendiri bangsa dan juga proklamator, atas dasar nurani dan kemampuannya dalam ilmu ekonomi dan pemahaman akan budaya gotong-royong yang tumbuh dalam keberagaman bangsa ini, telah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai Bapak Koperasi.
Kemana perginya kini koperasi yang benar-benar berciri gotong-royong? Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla dalam satu pengakuan menyatakan, kini “Banyak Masjid Bagus, tapi Masyarakatnya Kurang Makmur (MBM. Tempo, 31 Maret – 6 April 2025: 78 – 81).
Di negara yang warganya harus beragama ini, apa yang dikemukakan Jusuf yang mantan Wakil Presiden RI, bukan isapan jempol. bisa dibuktikan tidak hanya di gerbong KRL.
Di permukiman-permukiman, banyak warga yang tidak (mau) tahu tentang kondisi tetangganya yang mengalami kesusahan dan kesulitan hidup sehari-hari.
Bersyukur, mereka masih mau bercepat memberi perhatian ketika tetangga sakit, sakit berat, atau meninggal dunia. Toh dalam kondisi normal, mereka peduli tinggi ketika datang informasi menyedihkan dari negara negara lain. Yang dekat diabaikan, yang jauh lebih dipedulikan!.
Bahkan, ada pula Ketua RT yang tak peduli terhadap warganya yang menginginkan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunannya.
Padahal, ini merupakan kewajibannya sebagai warga negara.
Alasannya, saat ini untuk bayar PBB sudah bisa diketahui lewat gadget. Sebaliknya, sangat mencolok, dia akan bercepat ketika ada yang mau beli lahan di wilayahnya. Diketahui, jika transaksi lahan terjadi, dia akan mendapat keuntungan berupa “uang transaksi” plus hasil percaloan.
Kian renggangnya kerekatan antarwarga seperti itu, agaknya, memang sudah berlangsung sejak lama. Antropolog sangat senior, alm. Prof. Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (mulai terbit 1974) dalam kalimat yang bisa dipahami sebagai meragukan, menuliskan satu karangan dengan judul Apakah Nilai Gotong Royong itu Menghambat Pembangunan? (2015: 69).
Begitulah, agaknya, ketika pembangunanisme mengideologi secara kapitalistik bersama kemajuan teknologi.
TAG#PREMANISME, #POLRI, #TNI
215729591
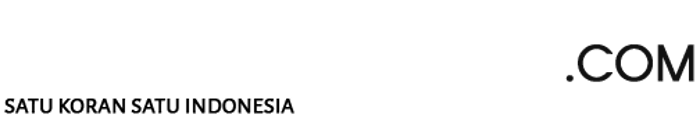
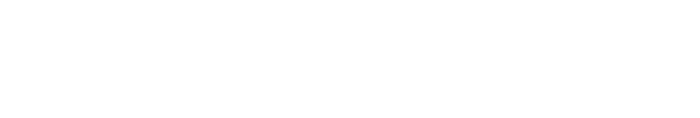





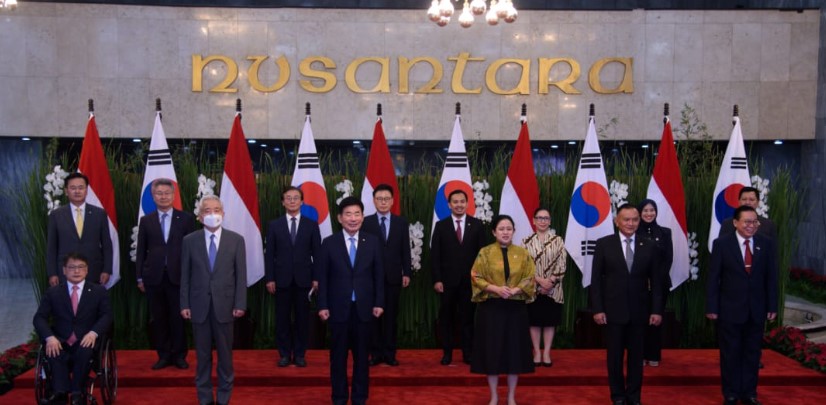










KOMENTAR