Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati, Soekarno dan Marhaen Petani dari Bandung Selatan

Oleh: Dian Kresnawati
Wasekjen DPN Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia
JAKARTA, INAKORAN
Apa yang membuat Sukarno bisa menjelaskan Marhaenisme dengan sangat baik?
Tentu saja, jawabannya: Marhaen. Marhaen dalam urain Sukarno sebagaimana di catat Cindy Adams dalam buku “Bung Karno:
Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” tidak sebatas pada nama petani yang dijumpainya saat bersepeda tanpa tujuan dan tiba-tiba telah sampai di bagian selatan Kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat.
Tiba-tiba saja Sukarno tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul di tanahnya, Sukarno kemudian menghampirinya dan bertanya “siapa pemilik tanah yang kau garap ini”? yang luasnya kurang dari sepertiga hektar.
Dalam perbincangan, diketahui sang petani menggarap tanah sendiri (bukan dibeli, bagian warisan orang tua), memiliki sekop, cangkul, bajak (alat produksi) sendiri, tetapi hasil yang didapatkan tidak ada yang bisa dijual, untuk makan bersama istri dan empat anak saja sudah susah (lengkapnya lihat edisi revisi buku penyambung lidah rakyat, 2007:73-81).
Sebelum pergi, Sukarno bertanya siapa nama petani itu. Si petani menjawab Marhaen. Di saat itu cahaya ilham melintas di otakku, ujar Sukarno. Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia! Semenjak itu kunamakan rakyatku Marhaen. Sukarno kemudian pamit, lanjut menghabiskan sisa hari itu dengan berkeliling Bandung.
Singkat cerita, Sukarno berkesimpulan bahwa Marhaen adalah rakyat kecil, tinggal di bumi ibu pertiwi, punya modal, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena ada sistem yang menindas (di miskinkan) oleh sistem.
Hal yang sampai hari ini menurut penulis mashi terjadi pada sebagian besar petani Indonesia, memiliki tanah kecil dan bahkan tak bertanah.
Dari sinilah, Sukarno menjadikan Marhaen sebagai simbol untuk rakyat kecil yang ditindas oleh sistem.
Entah itu petani, tukang becak, buruh, dan proletar lainnya. Mereka semuanya adalah kaum Marhaen.
Mereka semua telah ditindas oleh sistem penindasan dan mereka juga memiliki nasib yang sama. Namun disebagian rakyat Indonesia tak terkecuali yang mengaku Sukarnois perihal masih membedakan antara Marhaen dan Proletar. Jelas mereka ini tidak membaca serius buku-buku Sukarno.
Cerita Marhaen memiliki dampak, tidak hanya menjadi personifikasi bagi rakyat kecil. Akan tetapi menjadi ‘ideologi’ perlawanan pada kapitalisme--feodal. Lantas apa antara Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme.
Di dalam buku tersebut Sukarno telah menyampaikan perbedaan ketiga istilah tersebut tepatnya Pada Kongres Partindo yang diselenggarakan di Kota Mataram tahun 1933 yaitui:
(1) Marhaenisme yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Jadi Marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialisme;
(2) Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain;
(3) Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan Marhaenisme.
Kondisi Marhaen Pasca Indonesia Merdeka
Konteks tulisan ini, dipersempit pada kategori Petani seraya menyambut Hari Pangan se Dunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober.
Sukarno selalu mengingatkan bahwa “Petani adalah Soku Guru Bangsa”.
Apa yang diperjuangkan (Marhaenisme) melalui perjuangan politik nasionalisme untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan perikemanusiaan yang beradab pasca Indonesia merdeka masih jauh panggang dari api.
Dalam pandangan J. Eliseo Rocamora (liha, Nasionalimse Mencari Ideologi, 1991:149) bahwa ideologi yang dikonsepkan Sukarno tentang “sosial ekonomi” adalah membebaskan wong cilik dari belenggu kapitalisme--imperialismdan feodalisme lokal.
Namun, sekian puluh tahun setelah Sukarno jatuh, orde baru sampai era Joko Widodo, rasanya apa yang dicita-citakan Sukarno soal nasib petani terutama dari aspek ekonomi masih termarjinalkan.
Pemerintah belum sepenuhnya memerdekakan petani dari kemiskinan, kita menemukan pembangunan pertanian yang mendiskreditkan petani dan tidak berperspektif gender; singkat kata petani makin tidak berdaya.
BACA:
Hasto Sebut Jokowi Selesaikan Waduk di Banten yang Tak Diselesaikan Pak Harto
Jika kemiskinan petani di zaman orde lama atau masih era kolonialisme akibat operasi ideologi yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan masyarakat sebagai sumber tenaga kerja murah dan dilakukan dengan paksaan, maka sejak orba sampai detik ini, petani kita juga masih dikendalikan oleh korporasi besar pertanin, tengkulak (pengijon), dan pasar yang tidak adil.
Kemiskinan petani sudah terstigmatisasi sebagai akibat dari kemalasan petani bekerja, padahal persoalan kemiskinan mereka adalah karena sistem yang tidak memihak pada petani.
Menyitir pendapat James Scott bahwa petani Indonesia itu sangat rasional, tanggap terhadap teknologi dan ingin maju.
Namun ada faktor yang membatasi mereka yaitu penghasilan yang pas-pasan karena luas usaha yang relatif kecil.
Hal yang sama dijelaskan oleh William Collier (teori evolusi pertanian) bahwa keterlambatan dalam pembangunan pertanian disebabkan oleh hambatan faktor-faktor ekonomi seperti terbatasnya luas lahan, modal, dan kesalahan kebijakan pemerintah yang menganggap bahwa petani di Indonesia masih terbelakang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2020 menyebutkan bahwa tenaga kerja disektor pertanian berjumlah 38,22 juta dengan persebaran kelompok umur yaitu 17,29 persen atau 6,61 juta tenaga kerja pertanian berusia kurang dari 30 tahun; kemudian 29,15 persen atau 11,14 juta berusia 30-44 tahun, 32,39 persen atau 12,38 juta berusia antara 45-59 tahun, dan 21,7 persen atau 8,09 juta berusia di atas 60 tahun. Dari 38,22 juta tersebut sekitar 65,23 persen berpendidikan SD ke bawah. Dan 35,2 juta adalah petani dengan lahan sempit.
Data BPS selama tahun 2020 ekspor pertanian Indonesia mencapai 399,53 triliun atau naik 12,63 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 349,07 triliun.
Namun yang perlu menjadi perhatian, kontributor terbesar ekspor ini masih dari sawit bukan dari komoditas-komoditas khususnya pangan dan hortikultura.
Sementara Nilai Tukar Petani (NTP), rata-rata Nasional per Desember 2020 naik secara signifikan mencapai 103,25 atau naik 0,37 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 102,86 persen.
Fakta ini memperlihatkan bahwa bangsa kita masih lemah. Perlu direnungkan pidato Martin Luther King bahwa “kita tidak mungkin menjadi bangsa yang kuat selama kelompok terbesar masyarakat kita masih lemah”. Dan kelompok terbesar itu adalah petani.
Petani mempunyai hak asasi untuk merasakan kesamaan minimal dengan sesama warga dari kelas masyarakat lainnya. Negara harus menjamin bahwa petani tidak hidup dalam kesusahan, petani berhak merasakan dan menikmati kekayaan bumi pertiwi secara adil.
Negara, harus mengingat tak selamanya sejarah adalah milik yang kalah, suatu waktu sejarah itu akan jadi milik petani (pemenang). Apa yang dikatakan George Eliot bahwa tidak ada gerak mundur, bahkan kalau itu dipaksakan pada orang yang tidak berdaya dan terluka sekalipun, yang tidak mempunyai sisi yang buruk; sengatan matahari yang ditarik kembali itu sedang mengumpulkan kekuataan, pasti bisa.
Pangan Soal Hidup atau Mati Bangsa
Sukarno berkata, soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Sukarno menyadari betul bahwa rakyat yang lapar, tidak dengan serta merta kenyang hanya dengan dilemparkan kitab konstitusi.
Ia sadar rakyat yang lapar bisa memicu kerusuhan sosial bahkan dis-integrasi bangsa. Dalam perspektif lebih luas, politik luar negeri, pangan menempati posisi strategis, bisa menjadi senjata untuk memukul dan menguasai negara lain.
Seperti yang dikatakan Henry Kissinger (Mantan Menlu AS) kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat. Artinya di Abad 21 ini, bukan hanya minyak yang berpengaruh karena sumber energi manusia masih menggunakan bahan bakar fosil.
Sekarang ini bahan pangan pun bisa menjadi energi seperti bioethanol yang dibuat dengan teknik fermentasi biomassa. Kita perlu merenungkan ucapan Mahatma Gandhi “bagaimana negara bisa sepenuhnya merdeka, bila pangan rakyatnya tak bisa dicukupi sendiri”.
BACA:
Jumlah S2 dan S3 di Indonesia Ternyata cuma 8,31 Persen, dikit ya!
Pengelolaan pertanian pangan Indonesia masi direduksi dalam sudut pandang homo-economicus, baik yang berpihak pada kepentingan pemodal yang dibangun dalam narasi pertumbuhan maupun konteks pemerataan atas nama pembangunan.
Akibatnya pertanian seringkali diterjemahkan secara simplistik sebagai masalah-maslah ekonomi semata.
Misalnya produksi, distribusi, efisiensi, dan kesejahteraan. Pendekatan jalan keluarnya pun hanya diatasi dengan menggalakan cara-cara klasik seperti intensifikasi, peningkatan produktifitas dan seterusnya.
Jangka pendek pendekatan tersebut berguna namun bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah. Karena itu diperlukan sebuah refleksi yang lebih mendalam agar persoalan tidak semakin parah.
Disinilah kiranya pendekatan ekonomi politik perlu dinaikan keatas meja untuk melihat pembangunan pertanian Indonesia seperti yang sering disampaikan Sukarno.








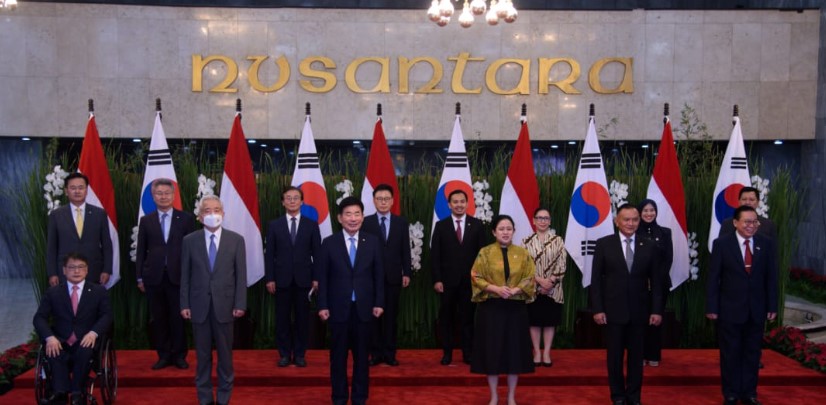





KOMENTAR